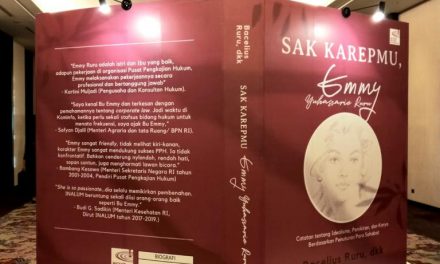Oleh: Kristin Samah
Jakarta (15/7/2023)—Sejak pertama kali ia diperkenalkan ibunya—salah satu sahabat terbaikku, Ida Farida Rivai (alm)—kami langsung cocok satu sama lain. Paling tidak dalam hal menertawakan kehidupan. Selisih umur hampir tidak pernah menjadi kendala. Apa saja bisa menjadi pemicu untuk terbahak-bahak.
Lalu jarak dan waktu membuat kami terpisah jauh. Ira menikah, melanjutkan studi ke Amerika, bekerja di sana, menjadi Associate Professor di Robert Morris University, Pittsburgh, United States, hingga punya sepasang anak yang ganteng dan cantik. Kabar tentangnya bukan hanya diperoleh dari Bu Ida yang selalu membanggakan putrinya, tetapi juga dari komunikasi langsung dengan Ira.
Pada anak saya, sebagai sesama jurusan Akuntansi, ia merasa menjadi ‘kakak asuh’. Satu kali, tanpa meminta persetujuan, ia katakan, sebelum memutuskan pindah kerja atau mau melanjutkan studi, Resa harus berkonsultasi dulu ke kakaknya. Tentu saja yang dimaksud dengan ‘kakaknya’ adalah Ira. Betapa seriusnya pembicaraan kami di antara tawa renyah yang selalu membuat tetangga sebelah iri.
Lalu peristiwa-peristiwa sedih menggulung kami. Soal rasa sakit, soal penyesalan, soal kematian, soal rasa kehilangan… Percakapan kami tidak pernah diiringi tangis. Tetap diselingi tawa. Mungkin saat itulah kami menyadari arti kata tawa hambar, pedih, dan garing.
“Aku lagi di Yogya Ira… menemukan sisa-sisa obat Ibuku… rasanya…”
Ia langsung menyambar… “Awas… jangan nangis Mbaaa…”
Kami tertawa… entah kutukan apa yang membuat bibir kami bisa berhaha, meskipun tahu, betapa banyak tusukan belati di dalam hati kami.

Lalu ia menceritakan nasib barang-barang yang ia kirim ke ibunya. Sebagian besar tersimpan rapih. Suaranya mulai bervibra ketika bercerita, giliran aku mengingatkan, “mulai deh… nangis deh…”
Kami berhaha lagi, saling menguatkan. Lalu menghentikan percakapan.
Setelah itulah aku menangis sejadi-jadinya… Mungkin Ira juga melakukan hal yang sama. Beginikah rasanya kehilangan orang yang sangat kami cintai?
“Ini semua buatmu,” aku menyorongkan tas bertulis Louis Vuitton, belum mengeluarkan isinya.

“Aku jadi malu…” katanya sambil membuka tas ransel, mengeluarkan paper bag bertulis Coach. Satu per satu barang dari tas bertulis Louis Vuitton aku keluarkan. Nih… bumbu pecel asli Blitar, keripik singkong buatan Solo, daster dari Pekalongan, dan foto masjid yang tetap kokoh berdiri dihantam tsunami. Dan tentu saja satu per satu barang itu langsung disambut tawa ngakak. Bumbu pecel, daster, dan keripik, semua merek LV. Syukurlah, Ira tidak memiliki kelakuan yang sama denganku. Di dalam, paper bag Coach memang benar-benar ada produk bermerek itu.
Setahun empat bulan dari kepergian Bu Ida, setahun sebelas bulan dari kepergian Ibuku, akhirnya kami bertemu. Dan seperti biasa, sejak detik pertama bertemu, kami sudah tertawa, layaknya tidak pernah ada beban berat dalam kehidupan kami. Lalu kami bercerita tentang kebaikan Bu Ida, ibunya, sahabat terbaik saya. Tanpa ada komando, kami menahan diri untuk tidak bersedih, meskipun semesta memahami arti getar suara, makna gerakan kepala agar mata tak saling beradu.
Kami bersyukur bisa melanjutkan nilai persahabatan Bu Ida, dan tentu saja Pak Rafki, suami Bu Ida, ayah Ira. Banyak sahabat Bu Ida, menjadi sahabat saya. Setiap kali saya ceritakan kalau saya bertemu dan bersahabat dengan sahabat-sahabat Bu Ida, ia mengucap syukur alhamdulillah. Begitu juga teman-teman saya yang bertugas ke Lampung, kota tempat tinggal Bu Ida, saya kirim untuk berkunjung, dan Bu Ida menyambut layaknya sahabat yang sudah lama tidak bertemu.
Saya tidak bisa berkirim Alfateha… tapi saya yakin, doa yang sama tulusnya, yang saya kirim untuk Bu Ida akan menjadi penghibur keluarga, dan membawa kedamaian untuk almarhumah.